A. DEFINISI AL-QUR’AN
Secara etimologi, al-Qur’an adalah mashdar dari kata qa-ra-a (قراً)sewazan dengan kata fu’lan (فعلا ن), artinya: bacaan; berbicara tentang apa yang tertulis padanya; atau melihat dan menelaah. Dalam pengertian ini, kata قر اً ن berarti maqru’ , isim maf’ul (objek) dari قراً . Hal ini sesuai denga firman Allah dalam surat al-Qiyamah (75):17-18:
Sesungguhnya atas tanggungan Kami-lah mengumpulkannya (di dadamu) dan (membuatmu pandai) membacanya.Apabila kami Telah selesai membacanya maka ikutilah bacaannya itu.
Al-Qur’an merupakan nama kitab suci yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad saw. Dalam kajian ushul fiqh, al-Qur’an juga disebut dengan al-Kitab, sebagaimana terdapat dalam surat al-Baqarah (2): 2:
Kitab (Al Quran) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertaqwa.
Dari segi terminology ditemukan beberapa definisi yang dikemukakan para ulama ushul fiqh, di antaranya adalah:
كلا م الله تعا لى النمزل على محمد صلى الله عليه و سلم با للفظ العر بي المنقو لِ اٍ لينا با لمصا حف, المتعبد بتلا و ته, المبد وء با لفا تحة و المختو م بسو رة النا س.
Kalam Allah yang diturunkan kepada Rasulullah Muhammad Saw. dalam bahasa Arab yang dinukilkan kepada generasi sesduahnya secara mutawatir, membacanya merupakan ibadah, terdapat dalam mushaf, dimulai dari surat al-Fatihah dan ditutup dengan surat al-Nas.
Dari definisi ini, para ulama ushul fiqh menyimpulkan ciri-ciri khas al-Qur’an, sebagai berikut:
1. Al-Qur’an merupakan kalam Allah yang diturunkan kepada Muhammad saw. Bukti bahwa al-Qur’an adalah kalam Allah adalah kemu’jizatan yang dikandung al-Qur’an itu sendiri, dari struktur bahasa, isyarat-isyarat ilmiah yang dikandungnya, dan ramalan-ramalan masa depan yang diungkap al-Qur’an.
2. Al-Qur’an diturunkan dalam bahasa Arab Qurasiy. Oleh karena itu, penafsiran dan terjemahan al-Qur’an tidak dinamakan al-Qur’an.
3. Al-Qur’an itu dinukilkan kepada generasi sesudahnya secara mutawawatir (diriwayatkan oleh orang banyak kepada umat Islam sampai sekarang). Oleh sebab itu, apabila tidak bersifat mutawatir, seperti al-qira’ah al-syadzdzah / القر ا ء ة الشا ذ ة (bacaan yang cacat) dan hadits (termasuk hadits qudsi) tidak dinamakan al-Qur’an. Para ulama ushul fiqh memberikan syarat-syarat untuk beberapa qira‘ah yang ada pada masa awal Islam, agar qira’ah itu dianggap sebagai al-Qur’an. Syarat-syarat qira’ah itu adalah:
1) Diriwayatkan dari Rasulullah saw. secara mutawatir.
2) Qira’ah itu sejalan dengan struktur bahasa al-Qur’an yang dipergunakan (ditentukan) Rasulullah saw.
3) Qira’ah itu sejalan dengan ketentuan bahasa Arab yang shahih.
4. Membaca setiap kata dalam al-Qur’an itu mendapat pahala dari Allah.
5. Ciri terakhir dari al-Qur’an yang dianggap sebagai suatu kehati-hatian bagi para ulama untuk membedakan al-Qur’an dengan kitab-kitab lainnya adalah bahwa al-Qur’an itu dimulai dari surat al-Fatihah dan diakhiri dengan surat al-Nas.
B. QIRA’AH AL-SYADZDZAH DALAM AL-QUR’AN
Berdasarkan syarat-syarat yang dikemukakan para ulama ushul fiqh di atas, maka qira’ah al-syadzdzah yang penuturannya dilakukan secara ahad yang tidak sampa ke tingkat mutawatir, sekalipun rangkaian penuturannya shahih, diperselisihkan para ulama ushul fiqh.Dari segi qira’at al-Qur’an terdapat perbedaaan. Dari hasil penelitian para ahli, tujuh di antaranya qira’at yang berkembang itu disepakati ke-mutawatir-annya. Itulah yang disebut qira’at yang tujuh/ qira’at sab’ah (قرا ء ة السبعة), yaitu:
1. Qira’at Ibnu Katsir, dari Mekah
2. Qira’at Ibnu ‘Amir, dari Syam
3. Qira’at Nafi, qari Madinah
4. Qira’at Abu ‘Amru, qari Bashrah
5. Qira’at ‘Ashim, dari Kufah
6. Qira’at Hmazah, qari Kufah
7. Qira’at al-Kisai, dari Kufah.
Dari segi hukum, apakah qira’ah al-syadzdzah seperti itu dapat dijadikan hujjah. Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat ulama.
1. Ulama Hanafiyyah dan Hanabilah mengatakan bahwa qira’ah al-syadzdzah bisa dijadikan hujjah yang sifatnya zhanni (relatif), apabila diketahui bahwa bacaan itu pernah didengar dari Rasulullah saw., karena hal tersebut termasuk Sunnah.
Alasan yang dikemukakan mereka adalah bahwa qira’ah al-syadzdzah meskipun periwayatannya tidak meyakinkan sebagai ayat al-Qur’an, namun setidaknya ia sama dengan hadits ahad; sedangkan hadits ahad dapat dijadikan sumber dalam mengistinbathkan hukum.
2. Ulama Malikiyyah dan Syafi’iyyah berpendapat bahwa qira’ah al-syadzdzah tidak dapat dijadikan hujjah, karena bacaan itu tidak termasuk al-Qur’an dan tidak mutawatir. Menurut mereka, qira’ah al-syadzdzah itu juga tidak bisa dimasukkan sebagai Sunnah, karena tidak ada riwayat pun yang menyatakan hal itu.
Alasan yang mereka kemukakan ialah bahwa Nabi Muhammad Saw. dituntut untuk menyampaikan ayat-ayat al-Qur’an yang diturunkan kepada beliau bagi sekelomok kaum yang tentu ucapan mereka merupakan kekuatan dalam menetapkan hukum. Sekelompok kaum seperti ini tidak akan mungkin bersamaan untuk tidak menukilkan apa yang mereka dengar dari Nabi. Periwayat yang membawa pesan wahyu dari Nabi, bila ia hanya seorang dengan mengatakan bahwa pesan yang ia bawa itu adalah al-Qur’an, mungkin ia salah. Dan jika tidak disebutkannya bahwa yang dia bawa adalah al-Qur’an, maka ia berada dalam keraguan antara apakah pesan itu khabar dari Nabi atau pendapatnya sendiri. Karena itu, tidak dapat dipegang sebagai hujjah yang kuat.
Perbedaan pendapat ulama tentang qira‘ah al-syadzdzah itu juga terjadi dalam hal boleh atau tidaknya dibaca dalam shalat. Perbedaan ini muncul karena yang disuruh dibaca dalam shalat adalah ayat al-Qur’an, sesuai dengan firman Allah dalam surat al-Muzammil (73): 20:
...Karena itu Bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran...
Ulama yang tidak meyakini qira’at al-syadzdzah sebagai al-Qur‘an tidak memperbolehkan membaca qira‘at al-syadzdzah dalam shalat, sedangkan ulama yang menganggap qira’at al-syadzdzah al-Qur’an, membolehkan membacanya dalam shalat.
Contoh (qira’at al-syadzdzah) bacaan ‘Abdullah ibn Mas’ud dalam ayat mengenai kaffarat sumpah:
فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَا مُ ثَلاَ ثَةِ أَ يَّا م مُتَتَا بِعَا ت...
…Maka barangsiapa yang tidak sanggup melakukan demikian, maka kaffaratnya puasa selama tiga hari (berturut-turut)... (Q.S. Al-Maidah (5): 89).
Kalimat mutatabi’at (berturut-turut) merupakan tambahan dari Ibn Mas’ud, dan bacaan seperti ini tidak mutawatir. Oleh sebab itu, menurut jumhur ulama, kalimat itu tidak termasuk al-Qur‘an.
C. BASMALAH DALAM AL-QUR’AN
Terdapat perbedaan pendapat ulama tentang keberadaan “basmalah“ dalam al-Qur’an. Para ulama tafsir, fiqh, dan khususnya ulama ushul fiqh sepakat menyatakan bahwa basmalah adalah salah satu ayat yang terdapat dalam surat an-Naml, 27:30. Dalam hal ini, sumber khabarnya bersifat mutawatir dan tidak terdapat perbedaan pendapat. Namun para ulama berbeda pendapat mengenai “basmalah” yang terdapat di luar surat an-Naml, yaitu pada setiap pembukaan surat dalam al-Qur’an, selain surat al-Taubah.
1. Imam Syafi’i berpendapat bahwa basmalah itu merupakan satu ayat dari surat al-Qur’an yang diawali oleh basmalah. Alasannya adalah:
1) Hadits riwayat Abdul Hamid dari Ja’far dari Nuhibn Abi Jalal dari Said al-Maqbari dari Abu Hurairah dari Nabi Muhammad Saw. yang mengatakan bahwa “Alhamdulillah” atau surat al-Fatihah terdiri dari 7 ayat, satu di antaranya adalah basmalah.
2) Hadits yang dikeluarkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam kitab shahihnya dari Umi Salamah bahwa Rasulullah membaca basmalah pada awal surat al-Fatihah dan surat-surat lainnya.
2. Imam Malik berpendapat bahwa basmalah di awal setiap surat bukan merupakan ayat dalam surat al-Qur’an. Juga bukan salah satu ayat dalam surat al-Fatihah atau surat lainnya. Alasannya bahwa umat Islam di Madinah tidak membca basmalah pada setiap surat dalam shalat yang mereka lakukan. Prkatik yang demikian itu sudah berlaku semenjak masa Nabi sampai masa Imam Malik, padahal dalil untuk membaca al-Fatihah dalam shalat adalah pasti. Kebiasaan penduduk Madinah yang tidak membaca basmalah dalam shalat itu diperkuat dengna hadits Nabi yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Anas ibn Malik yang mengatakan;”Saya shalat di belakang Nabi, juga di belakang Abu Bakar,’Umar dan ‘Utsman; mereka memulai bacaan al-hamdulillah dalam shalat dengan “Alhamdulillah”.
3. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa basmalah itu merupakan salah satu ayat dalam al-Qur’an, namun bukan salah satu ayat dalam surat al-Fatihahdan awal-awal surat lainnya dalam al-Qur’an. Menurut mereka basmalah diturunkan Allah untuk menjadi pemisah antara satu surat dengan surat sesudahnya. Alasan mereka adalah sebuah riwayat dari Ibn ‘Abbas yang mengatakan,“Rasulullah Saw. tidak mengetahui penutup satu surat dan pembuka surat berikutnya, sampai suatu ketika datang Jibril membacakan bismililahi al-rahmani al-rahim pada awal setiap surat.” (H.R. Abu Daud, al-Baihaqi, dan al-Hakim).
Oleh karena yang disuruh dibaca dalam shalat adalah al-Qur’an seperti tersebut dalam ayat di atas, sedangkan kedudukan basmalah sebagai bagian dari al-Qur’an diperselisihkan, maka terdapat pula perbedaan dalam hal membacanya dalam shalat.
1) Ulama yang mengatakan bahwa basmalah merupakan bagian dari surat al-Qur’an membolehkan membaca basmalah dalam shalat.
2) Ulama yang mengatakan bahwa basmalah bukan bagian dari al-Qur’an tidak membolehkan membacanya dalam shalat, baik secara jahar (kasar) maupun secara sir (perlahan).
3) Ulama yang mengatakan bahwa basmalah adalah al-Qur’an tetapi tidak termasuk bagian surat membolehkan membaca basmalah dalam shalat tetapi hanya sir, tidak boleh di-jahar-kan.
D. PENUNJUKAN LAFADZ TERHADAP MAKNA AL-QUR’AN
Menurut ulama Hanafiyah, penunjukan lafadz terhadap makna dapat dibedakan menjadi empat yaitu:
1. Dilalat al-Ibarat
2. Dilalat al-Isyarat
3. Dilalat al-Dilalat
4. Dilalat al-‘Iqtidla.
1. Dilalat al-Ibarat
Dilalat al-Ibarat adalah penunjukan lafadz terhadap makna secara tidak piker panjang; berdasarkan susunannya, diketahui terdapat maksud pokok dan maksud tambahan.
Salah satu ayat yang dijadikan contoh dalam rangka memperjelas dilalat al-ibarat adalah firman Allah:
Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja… (Q.S. An-Nisa (4): 3).
Dari segi susunan kalimat (siyaq al-kalam), maksud pokok dalam ayat tersebut adalah kewajiban mengawini seorang istri saja apabila khawatir tidak akan mampu berlaku adil. Akan tetapi, bisa jadi yang dijadikan makna pokok dalam ayat tersebut adalah pembatasan jumlah istri dalam satu periode, yaitu empat orang. Sedangkan maksud tambahan dari ayat tersebut adalah kebolehan menikahi wanita-wanita yang dicintai.
2. Dilalat al-Isyarat
Ini adalah penunjukan lafadz terhadap makna (berdasarkan cakupannya) tanpa disengaja untuk itu, berdasarkan susunan kalimatnya; ia memerlukan pendalaman (baik sedikit maupun banyak) untuk mendapatkan makna tersembunyi tersebut.
Salah satu ayat yang dijadikan contoh oleh ulama dalam menjelaskan dilalat al-isyarat adalah ketentuan Allah tentang kebolehan menceraikan istri sebelum dijima’. Allah berfirman:
Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya… (Q.S. Al-Baqarah(2): 236).
Dalam ayat tersebut terdapat dua maksud yang secara mudah dapat diperoleh yaitu: pertama, kebolehan menceraikan isteri sebelum disetubuhi; kedua, kebolehan cerai sebelum menentukan jenis dan jumlah mahar. Itu adalah maksud pokok yang didapatkan berdasarkan susunan kalimat. Sedangkan makna yang tersembunyi (isyarat) adalah bahwa nikah itu sah tanpa penentuan jumlah dan jenis mahar yang merupakan hak isteri; sebab talak tidak pernah ada tanpa pernikahan yang sah.
3. Dilalat al-Dilalat
Adalah penunjukan lafadz terhadap keterlampauan batas hukum yang tersurat kepada yang tersirat karena adanya kesamaan ‘illat yang secara bahasa orang mengetahui bahwa ia adaloah manath al-hukm.
Contoh:
Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, Sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka). (Q.S. An-Nisa (4): 10).
Dilalat al-ibarat (maksud/ penunjukan pokok) ayat tersebut adalah cegahan untuk memakan harta anak yatim tanpa cara yang benar. Ulama berpendapat bahwa ‘illat cegahan tersebut adalah kelaliman. Oleh karena itu, setiap bentuk kelaliman terhadap harta anakk yatim (dimakan, dibakar, dirusak, ataupun dimusnahkan) itu dilarang oleh Allah.
4. Dilalat al-Iqtidla
Yang dimaksud dilalat al-iqtidla adalah penunjukan kalimat terhadap makna yang tidak disebutkan; yang kalimat itu dapat dimengerti dengan baik apabila perkiraan maknanya sudah didapatkan, atau kalimat itu tidak dapat ditegakkan kecuali dengan menjelaskan makna yang tersembunyi tersebut.
Contoh:
Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu... (Q.S. An-Nisa (4): 23).
Dalam ayat tersebut terdapat pernyataann yang mengatakan bahwa ibumu haram bagimu. Haram diapakan: haram dicium,haram dicintai, haram ditolong atau haram yang lainnya? Karena pertanyaan-pertanyaan itulah kemudian ulama menafsirkan ayat tersebut dengan mengatakan bahwa mengawini ibu sendiri hukumnya haram. Oleh karena itu, penafsiran ayat tersebut adalah:
Ulama Syafi’iyyah membagi penunjukkan lafadz terhadap makna menjadi dua macam yaitu:
1. Dilalat al-Manzhum
2. Dilalat Ghair Manzhum
1. Dilalat al-Manzhum
Dilalat al-Manzhum adalah penunjukkan lafadz (secara jelas) terhadap makna, baik penunjukkan itu terhadap semua makna maupun sebagiannya.
Contoh:
...Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...(Q.S. Al-Baqarah (2): 275).
Dalam ayat di atas terdapat pernyataan yang sangat jelas, yaitu bahwa jual-beli itu halal; sedangkan riba itu haram. Hal seperti itulah menurut ulama Syafi’iyyah termasuk dilalat al-manzhum.
2. Dilalat Ghair Manzhum
Adalah penunjukkan kalimat terhadap makna dengan menggunakan lafadz yang tidak sharih.
Contoh:
… dan ibunya mengandung dan menyapihnya selama tiga puluh bulan... (Q.S. Al-Ahqaf (46):15).
Ayat tersebut kemudian dihubungkan dengan firman Allah yang lain, yaitu:
...dan ibunya telah menyapihnya selama dua tahun... (Q.S Luqman (31):14).
Dalam ayat yang pertama, terdapat informasi bahwa ibu mengandung dan menyusui anaknya selama 30 bulan (dua tahun enam bulan); sedangkan dalam ayat yang kedua, terdapat informasi bahwa ibu mengasuh anaknya selama dua tahun. Oleh karena itu, kemudian ulama Syafi’iyyah bekesimpulan bahwa durasi hamil yang terpendek adalah enam bulan (30 bulan dikurangi 24 bulan).
Dua ayat tersebut tidak dimaksudkan untuk menyatakan bahwa durasi hamil yang terpendek adalah dua bulan. Oleh karena itu, ulama Syafi’iyyah menyebutnya sebagai makna yang tersembunyi yang tidak dimaksudk oleh pembicara (Allah), tetapi ia mesti ada. Cara berfikir seperti ini, sama dengan dilalat al-isyarat yang dikemukakan oleh ulama Hanafiyah.
KESIMPULAN
Dari semua penjelasan di atas dapatlah kiranya disimpulkan bahwa al-Qur’an al-Karim adalah sumber dan dalil paling sentral dalam mengistinbath hukum Islam. Karena bersifat sentral, maka ia mutlak kebenarannya. Kehujjahan al-Qur’an secara lafadz memang disepakati oleh para ulama ushul fiqh, ia bersifat qat’i dan mutawatir. Namun dari sisi lain, kehujjahan al-Qur’an menimbulkan perbedaan di kalangan ulama ushul fiqh dalam menetapkan sebuah hukum. Beberapa perbedaan ulama ushul fiqh yaitu mengenai qira’at al-syadzdzah, kedudukan basmalah, dan dilalat al-lafadz. Dengan adanya berbagai perbedaan itu, maka berbeda pula ketetapan hukum yang dihasilkan oleh para Imam Mazhab.
SARAN
Demikianlah sedikit uraian tentang Keragaman Otentisitas al-Qur’an di Kalangan Mazhab Sunni dalam diskursus Perbandingan Mazhab dalam Ushul Fiqh. Tentunya tulisan ini masih sangat jauh untuk mengungkap secara komprehensif dan sempurna tentang Keragaman Otentisitas al-Qur’an dalam khazanah Ilmu Perbandingan Mazhab dalam Ushul Fiqh . Penulis hanya menyusun dari literatur yang masih terbatas sifatnya. Penulis harap para pembaca untuk membaca referensi buku yang berkenaan dengan ilmu ini untuk mendapatkan penjelasan dan ilmu yang lebih lengkap dari ini.
DAFTAR PUSTAKA
Al-Qur’an al-Karim
Haroen, Nasrun. 1996. Ushul Fiqh 1. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
Mubarok, Jaih. 20002. Metodologi Ijtihad Hukum Islam. Yogyakarta: UII Press.
Syarifuddin, Amir . Ushul Fiqh, I . Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
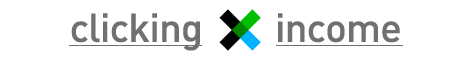




0 komentar:
Posting Komentar