Globalisasi kini telah dimulai. Masyarakat di seluruh dunia menjadi saling tergantung pada semua aspek kehidupan baik secara budaya, ekonomi, maupun politik. Terutama dalam aspek budaya, batasannya kini telah kabur. Bagi dunia pendidikan, era yang semacam ini merupakan tantangan tersendiri. Untuk itu, tulisan ini ingin menekankan kembali pentingnya nilai-nilai akhlak yang tetap harus diutamakan dalam proses pendidikan. Dalam rangka menyiapkan manusia yang tetap memegang nilai-nilai akhlak di era globalisasi, walaupun tidak boleh sendirian, lembaga pendidikan tetap memegang peranan yang utama. Dengan demikian, dalam prakteknya, lembaga pendidikan mempunyai peran ganda, satu sisi yang sudah menjadi tugas pokoknya, yaitu membentuk anak didik yang berkepribadian, dan sisi lain bagaimana peserta didik dapat bersaing dengan dinamika tantangan dunia global.
PENDAHULUAN
Sudah semestinya apabila pembentukan akhlak mulia harus tetap diprioritaskan dalam tujuan penyelenggaraan pendidikan. Namun, seiring lajunya zaman rasanya semakin berat tantangan dunia pendidikan ini dalam rangka menyiapkan manusia yang mempunyai akhlak mulia. Diketahui, bahwa pada era globalisasi ini, batas-batas budaya sulit dikenali. Oleh karena itu, tugas dunia pendidikan semakin berat untuk ikut membentuk bukan saja insan yang siap berkompetisi, tetapi juga mempunyai akhlak mulia dalam segala tindakannya sebagai salah satu modal sosial (capital social). Agar terbentuknya insan yang berakhlak mulia, tentu saja ada suatu tuntutan bagaimana proses pendidikan yang dijalankan mampu mengantarkan manusia menjadi pribadi yang utuh, baik secara jasmani maupun rohani. (Sudarwan Danim, 2006: 65).
Lebih dari itu, dunia pendidikan masih dihadapkan pada kerusakan yang tengah dialami bangsa Indonesia, yaitu permasalahan “krisis multidimensi”. Artinya, krisis yang tengah melanda bangsa ini tidak hanya dalam bidang financial moneter (keuangan) semata, melainkan juga adanya pengelolaan yang lemah (weak governance) dalam urusan pemerintahan serta kekuasaan, sehingga semakin merambah meliputi semua segi kehidupan bangsa (Nurcholish Madjid, 2004: 113). Untuk itu, penegakan akhlak yang mulia harus menjadi agenda yang tidak boleh dikesampingkan, karena lemahnya akhlak inilah yang tampaknya menyebabkan bangsa ini mengalami krisis multidimensi. Dapatlah diamati, KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme) yang menjadi penyakit bangsa ini sulit dihentikan, seakan-akan telah menjadi suatu budaya. Bahkan pada era reformasi ini ditemui, untuk tidak mengatakan banyak, orang yang awalnya meneriakkan “hentikan korupsi”, sekarang sebaliknya malah dia sendiri yang melakukan KKN. Seakan-akan dia berteriak karena belum mendapat bagian kue, dan ketika giliran mendapatkannya lantas diam. Melihat kedaan semacam ini, tidaklah berlebihan apabila salah satu perioritas garapan dunia pendidikan adalah mengatasi krisis akhlak yang tengah melanda bangsa ini. Namun, terkadang memang terasa ironis, disebabkan kebanyakan yang melakukan tindak korupsi atau berprilaku tak berakhlak adalah mereka orang-orang yang “terdidik”. Mereka adalah orang yang pernah mengenyam dunia pendidikan, yang rata-rata pernah duduk di tingkat pendidikan menengah lanjutan sampai perguruan tinggi, bahkan tingkat doktoral. Pertanyaannya adalah, apakah hal tersebut menandakan kurang berhasilnya dunia pendidikan bangsa Indonesia? Atau, perilaku yang semacam ini sudah menjadi mental kebanyakan masyarakat bangsa Indonesia, sehingga sulit disembuhkan. Terlepas dari semua itu, tetap bahwa pendidikan akhlak atau pendidikan humaniora harus dikedepankan. Dengan demikian, tidak semestinya terdengar atau keluar perkataan “putus asa”.
GLOBALISASI DAN TANTANGANNYA
Globalisasi secara umum, sebagaimana diungkapkan Sztompka (2004: 101-102), dapat diartikan sebagai proses yang menghasilkan dunia tunggal. Artinya, masyarakat di seluruh dunia menjadi saling tergantung pada semua aspek kehidupan baik secara budaya, ekonomi, maupun politik, sehingga cakupan saling ketergantungan benar-benar mengglobal. Misalnya, dalam bidang politik, globalisasi ditandai dengan adanya kesatuan supranasional dengan berbagai cakupan blok politik dan militer dalam NATO (North Atlantic Organizatioan), koalisi kekuasaan dominan, dan organisasi berskala internasional seperti PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa).
Selanjutnya, globalisasi dalam bidang ekonomi ditandai dengan peningkatan peran koordinasi dan integrasi supranasional, seperti EFTA (European Free Trade Association), EC (European Commission), OPEC (Organization of the Petroleum Exporting Countries), perjanjian kerja sama ekonomi regional serta dunia, pembagian kerja dunia, dan peningkatan peran kerja sama multinasional (Piötr Sztompka, 2004: 102-103). Mansour Fakih (2002: 219) menambahkan bahwa globalisasi di bidang ekonomi dapat dipahami sebagai suatu proses pengintegrasian ekonomi nasional berbagai bangsa ke dalam sistem ekonomi global. Oleh karena itu, sejak dicanangkannya penandatanganan kesepakatan GATT (General Agreement on Tariff and Trade), ditandatanganinya aneka kesepakatan lainnya, seperti NAFTA (The North American Free Trade Agreement), APEC (Asia Pasific Economi Conference), serta WTO (World Trade Organization), dan dilaksanakannya Structural Adjustment Program oleh Bank Dunia, pertanda globalisasi tengah berlangsung. Sebenarnya, ditinjau dari sejarah perkembangan ekonomi, pada dasarnya globalisasi merupakan salah satu fase perjalanan panjang perkembangan kapitalisme liberal, yang secara teoritis telah dikembangkan oleh Adam Smith. Dengan demikian, sesungguhnya globalisasi merupakan kelanjutan dari kolonialisme dan developmentalism (Mansour Fakih, 2002: 211).
Sementara itu, globalisai di bidang budaya ditandai dengan kemajuan menuju keseragaman. Dalam hal ini, media massa, terutama televisi, mengubah dunia menjadi sebuah “dusun global”. Informasi dan gambaran peristiwa yang terjadi di tempat yang sangat jauh dapat ditonton jutaan orang pada waktu hampir bersamaan, sehingga pengalaman budaya, seperti selera, persepsi, dan pilihan relatif sama. Di samping itu, muncul juga bahasa Inggris sebagai bahasa global yang berperan sebagai alat komunikasi profesional di bidang bisnis, ilmu pengetahuan, komputer, teknologi, transportasi, dan digunakan sebagai alat komunikasi pribadi dalam berpergian. Di bidang teknologi komputer, program yang sama digunakan di seluruh dunia sebagai pola umum dalam menyusun dan memproses data serta informasi. Akhirnya, tradisi budaya pribumi atau lokal semakin terkikis dan terdesak, serta menyebabkan budaya konsumen atau budaya massa model Barat menjadi budaya universal yang menjalar ke seluruh dunia (Piötr Sztompka, 2004: 102-103).
Pengertian globalisasi di atas tidak jauh berbeda dengan apa yang pernah dikemukakan Irwan Abdullah (2006: 107). Menurutnya, budaya global ditandai dengan adanya integrasi budaya lokal ke dalam suatu tatanan global. Nilai-nilai kebudayaan luar yang beragam menjadi dasar dalam pembentukan sub-sub kebudayaan yang berdiri sendiri dengan kebebasan-kebebasan ekspresi. Globalisasi yang ditandai oleh perbedaan-perbedaan dalam kehidupan telah mendorong pembentukan definisi baru tentang berbagai hal dan memunculkan praktik kehidupan yang beragam. Proses integrasi masyarakat ke suatu tatanan global yang dianggap tidak terelakan inilah yang akan menciptakan suatu masyarakat yang terikat dalam suatu jaringan komunikasi internasional yang begitu luas dengan batas-batas yang tidak begitu jelas. Dengan demikian, selain arus orang dan barang, arus informasi merupakan suatu keuntungan dan sekaligus suatu ancaman yang sangat berbahaya. Misalnya, terbentuknya diversitas (perbedaan), pembentukan nilai jangka panjang, dan hilangnya humanitas (perikemanusiaan) (Irwan Abdullah, 2006: 166).
Secara jelas pada era globalisasi ini, sebagaimana yang sekarang terjadi, dunia seolah sudah tidak memiliki lagi batas-batas wilayah dan waktu. Food, fashion, dan fun (makanan, mode, dan hiburan) merupakan gejala yang sangat kentara pada era ini. Food berarti orang tidak lagi makan makanan dari daerahnya, karena banyak makanan dan minuman disajikan secara sama di seluruh dunia. Misalnya, resep Kolonel Sanders dari Kentucky Fried Chicken dapat dinikmati baik oleh penduduk Chicago maupun penduduk berbagai pelosok Indonesia sekalipun. Fashion menandakan bahwa sekarang terdapat kota-kota tertentu yang menentukan perkembangan busana untuk seluruh dunia. Semacam ini dapat dilihat dalam majalah mode Prancis Elle yang dicetak dalam enam belas edisi internasional. Demikian pula, CNN (Cable News Network) yang merupakan stasiun televisi internasional melaporkan mode-mode baru dari New York, Tokyo, Milan, dan Paris. Selanjutnya, fun berarti sekarang hiburan menjadi bisnis internasional, seperti film, musik, dan macam-macam kegiatan hiburan lainnya dikelola secara internasional (Jalaluddin Rakhmat, 2003: 71-72). Di belahan separuh dunia, orang secara jelas dan mudahnya dapat berbicara melalui telepon dikarenakan adanya fasilitas satelit. Dalam hal ini, berbagai orang dapat menyaksikan Pertandingan Sepak Bola Piala Dunia secara langsung di Dortmun, Jerman, lewat Satelit siaran langsung di televisi. Orang juga bisa berbicara lewat tulisan melalui internet, yang berarti tanpa ada sensor dari tangan siapapun. Dengan alat canggih tersebut, keglamouran dan kebebasan berlebihan yang terjadi di Hollywood, Amerika Serikat detik itu juga bisa disaksikan, misalnya, di Indonesia dalam waktu yang bersamaan (A. Qodri Azizy, 2004: 19-20). Melalui internet, orang juga dengan bebas dapat mengakses gambar-gambar tubuh manusia secara vulgar, dan bahkan dengan adegan-adegan yang dapat merusak pikiran manusia.
Fenomena globalisasi memang sudah tidak dapat dihindari lagi oleh siapapun, kecuali dia sengaja mengungkung diri menjauhi interaksi dan komunikasi dengan yang lain. Hanya saja yang perlu disadari dan mendapat catatan, di samping globalisasi membawa manfaat, namun juga mendatangkan madlarat. Oleh karena itu, harus pandai-pandai menyikapinya, misalnya, jikalau nilai-nilai yang terdapat dalam globalisasi itu positif maka tidaklah salah untuk mengambilnya, sebaliknya jika hal itu memang negatif maka harus dapat membendungnya. Dalam hal ini, ungkapan seperti al-akhdu bi al-jadid al-aslah (ambillah hal-hal yang baru yang sekiranya baik dan banyak mengandung maslahat) mungkin dapat dijadikan dasar pijakan. Sebagaimana diungkapkan Azizy (2004: 25), apabila globalisasi itu memang memberi hal-hal, nilai, dan praktek yang positif yang tidak berbenturan dengan budaya lokal, nasional, dan terutama sekali nilai agama, haruslah menjadi tantangan bagi bangsa Indonesia untuk mampu menyerapnya. Dengan kata lain, bagaimana agar nilai-nilai positif yang ada di Barat, atau bahkan di belahan negara lain yang masuk dapat dipraktekkan di tengah-tengah masyarakat. Budaya positif tersebut mencakup disiplin, kebersihan, tanggung jawab, egalitarianisme, kompetisi, kerja keras, penghargaan terhadap orang lain yang membutuhkan bantuan, demokratisasi, dan semacamnya. Sebaliknya, yang harus disadari, globalisasi juga banyak mengandung hal-hal yang negatif. Misalnya, karena globalisasi mengaburkan batas-batas budaya, akibatnya aneka budaya seluruh umat di jagat raya ini mudah diakses dan ditiru lewat media televisi maupun internet. Oleh karena itu, dengan mudah orang mengakses gaya, model, prilaku, atau cara berbusana yang pada hakikatnya bertentangan dengan nilai-nilai akhlak yang mulia. Dampak yang tidak baik pun dapat dirasakan, terutama bagi kalangan anak-anak dan kaum remaja. Dapatlah disaksikan, bahwa budaya yang semacam itu, yang kebanyakan terjadi di Barat dan tidak terkecuali di Indonesia, telah membawa prilaku sex bebas, sebuah prilaku yang tidak bertanggung jawab.
PENDIDIKAN DAN ERA GLOBALISASI
Telah dikemukakan bahwa pendidikan merupakan salah satu sarana yang dapat dijadikan pengembangan modal sosial (social capital). Modal sosial sendiri dapat berarti SDM (Sumber Daya Manusia) yang mempunyai kejujuran, kepercayaan, kesediaan, dan kemampuan untuk bekerjasama, berkoordinasi, penjadwalan waktu dengan tepat, dan kebiasaan untuk berkontribusi dalam upaya pembangunan (Ardi Kapahang dkk., 2001). Menurut Fukuyama (1999), modal sosial adalah serangkaian nilai atau norma sosial yang dihayati oleh anggota kelompok, yang memungkinkan terjadinya kerja sama antara para anggotanya. Lebih lanjut diketahui, bahwa salah satu modal sosial yang terpenting adalah adalah trust, yakni keyakinan bahwa para anggota masyarakat dapat saling berlaku jujur dan dapat diandalkan.
Jadi, pengembangan modal sosial dapat berarti terciptanya insan yang sempurna. Jika ini yang diharapkan, berarti era globalisasi merupakan tantangan sendiri. Pada era ini lembaga pendidikan, di samping harus menciptakan SDM yang mampu berkompetensi dan berprestasi, juga harus dapat menyiapkannya agar mampu menghadapi akulturasi budaya yang luar biasa, terutama dari negara-negara Barat. Artinya, pada era globalisasi ini dunia pendidikan dituntut mempunyai peran ganda. Pertama harus mempersiapkan manusia yang berkualitas dan mampu berkompetisi sesuai dengan kemajuan ilmu dan teknologi, atau manusia yang mempunyai kesiapan mental dan sekaligus kesiapan kemampuan skill (profesional). Kedua, yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana dunia pendidikan ini mampu menyiapkan manusia yang berakhlak mulia. Dengan demikian, pada satu sisi, proses pendidikan harus dapat menyiapkan anak didik yang dapat menyesuaikan diri dengan masyarakat sekarang dan akan datang, masyarakat yang semakin lama semakin sulit diprediksi karakteristiknya. Hal ini dikarenakan di era kehidupan global ini, dengan adanya berbagai penemuan dalam bidang teknologi informasi, orang harus dapat membelajarkan diri dalam suatu proses pendidikan yang bersifat maya (virtual). Implikasinya, bahwa pendidikan harus mampu mempersiapkan bangsa ini menjadi komunitas yang terberdayakan dalam menghadapi kehidupan global yang semakin lama semakin menggantungkan diri pada teknologi informasi (Suyanto, 2004). Sisi lain, proses pendidikan tidak boleh mengenyampingkan pembentukan kepribadian. Masyarakat sekolah haruslah masyarakat yang berakhlak. Kampus, misalnya, bukan semata-mata hanya wahana untuk meningkatkan kemampuan intelektual, tetapi juga kejujuran, kebenaran, dan pengabdian pada masyarakat. Secara keseluruhan budaya kampus adalah budaya yang berakhlak mulia. Kampus semestinya menjadi pelopor dari perubahan kebudayaan secara total yang bukan hanya nilai-nilai ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi juga tempat persemaian dari pengembangan nilai-nilai akhlak kemanusiaan (Tilaar, 2002: 76).
Pendidikan memang erat kaitannya dengan pembentukan mental yang berakhlak. Sebagaimana digariskan oleh kaum eksperimentalis, bahwa pendidikan itu tidak hanya berarti memberikan pelajaran kepada subjek didik agar dapat menyesuaikan diri terhadap situasi kehidupan nyata, tetapi lebih dari itu adalah tempat meningkatkan kualitas hidup manusia dengan mempertinggi pengalaman moral (Imam Barnadib, 1996: 20). Demikian pula, aliran esensialisme dan perenialisme menyatakan, bahwa di samping proses pendidikan bertujuan untuk pembentukan kecerdasan, tetapi juga bagaimana pendidikan dapat membentuk tingkah laku yang cerdas sebagai tujuan utama. Mereka tidak memungkiri kenyataan bahwa pendidikan itu adalah sarana tempat pembentukan watak atas nilai-nilai budaya yang luhur. Sementara itu, terbentuknya watak, kepribadian, dan kualitas manusia yang lain tidak dapat dilepaskan dari kecerdasan tingkah laku seseorang (Imam Barnadib, 1996: 36). Dari arti pendidikan tersebut menunjukkan, bahwa masalah akhlak (pembentukan kepribadian) adalah tidak dapat ditinggalkan, bahkan menjadi tujuan utama pendidikan. Dikatakan, tujuan primer dan tertinggi usaha pendidikan adalah peningkatan (tarbiyah) nilai kesucian manusia dalam fitrahnya yang dianugerahkan Tuhan. Setelah itu, baru mengarah kepada tujuan sekunder yang semata-mata untuk menopang tujuan primer tersebut, yaitu sebagai investasi modal manusia (human capital investment) dengan dua macam dampaknya. Pertama, dampak peningkatan kemampuan kerja dengan keahlian dan profesionalisme. Kedua, berkaitan dengan tujuan pokok pendidikan itu sendiri sesuai dengan bidang-bidang yang dikembangkannya, seperti teknologi, kesehatan, manajeman, pertanian, keguruan, dan sebagainya (Nurcholis Madjid, 2004: 149).
Intinya, di alam era globalisasi ini, tugas pendidikan, khususnya di Indonesia, di samping harus mampu menyiapkan manusia yang mampu berkompetisi, tetapi juga harus mampu menyiapkan peserta didik agar dapat menghadapi akulturasi budaya yang luar biasa, terutama dari Barat. Namun, perlu ditekankan, sebenarnya derasnya arus budaya manca negara ke Indonesia bukanlah presenden buruk bagi rakyat apabila mampu menyaring, mengambil yang baik, dan meninggalkan yang buruk (M. Imam Zamroni, 2004: 213) Pendidikan harus dapat berperan sebagai alat yang ampuh untuk menyaring budaya-budaya yang masuk dan sekaligus menguatkan budaya lokal yang memang masih perlu dijunjung. Dengan demikian, lembaga pendidikan dituntut, misalnya, harus menciptakan kurikulum yang dapat memberdayakan tradisi lokal, supaya tidak punah karena akibat pengaruh globalisasi yang tidak lagi mengenal sekat-sekat primordial dan batas-batas wilayah bangsa.
Sementara itu, para pendidik yang berposisi sebagai sumber nilai, harus orang yang selalu dapat ditaati dan diikuti (Mochtar Buchori, 1994: 105). Untuk itu, pendidik dituntut harus selalu berusaha membekali dirinya agar dapat menjadi tauladan. Sebagai orang yang berilmu, pendidik semestinya harus selalu menghindarkan diri dari segala akhlak dan perbuatan yang tercela, memelihara diri dari kenistaan, seperti tamak (mengharap sesuatu dari orang lain secara berlebih-lebihan), sehingga tidak menimbulkan kesan yang hina terhadap ilmu dan sifat ilmuwan yang disandangnya. Demikian pula, orang yang berilmu hendaknya bersifat tawadlu (merendahkan 13 hati tetapi bukan minder), dan jangan bersifat sebaliknya (sombong), serta haruslah memiliki sifat iffah (memelihara diri dari beragam barang haram dan tidak baik) (Miftahuddin, 2006: 245). Tidak salah dalam hal ini apabila para pendidik menengok kembali apa yang pernah dikatakan Al-Zarnuji, bahwa
“wayambaghî li ahli al-ilmi an lâ yadzilla nafsahu bi al-tam‘i fi ghairi matma‘in wa yataharraza ‘ammâ fîhi madzallatu al-‘ilmi wa ahlihî, wa yakûnu mutawadi‘an –wa al-tawada‘u baina al-takabburi wa al-madzallati – wa al-‘iffahtu” (al-Zarnuji, t.th.: 11-12).
Artinya, “sebaiknya bagi orang yang berilmu, janganlah membuat dirinya sendiri menjadi hina lantaran berbuat tamak terhadap sesuatu yang tidak semestinya, dan hendaknya menjaga dari perkara yang dapat menjadikan hinanya ilmu dan para pemegang ilmu, sebaliknya, berbuatlah tawadlu (sikap tengah-tengah antara sombong dan kecil hati) dan iffah.” Para pendidik diharapkan pula tidak bersikap dan berbuat sebagaimana digambarkan dalam al-Qur‟an, yang berbunyi: “Yâ ayyuha al-ladzîna âmanu lima taqūluna mâ lâ taf’alûn. Kabura maqtan ‘inda Allah an taqûlû mâ lâ taf’alûn”. Artinya, “hai orang-orang beriman, mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu perbuat. Amat besar kebencian di sisi Allah ketika kamu mengatakan apa yang tidak kamu perbuat” (Q.S. Ash Shaff: 2-3).
Selanjutnya, dapat diyakini bahwa pendidikan formal saja sebagai sarana tempat proses pendidikan dijalankan, misalnya, dari TK (Taman Kanak-kanak) sampai perguruan tinggi, tidaklah memadai terutama sebagai sarana membekali peserta didik agar tidak terjerumus dalam tingkah laku yang tidak berakhlak. Oleh karena itu, segenap komponen masyarakat harus andil dalam proses pendidikan ini, walaupun peran utama tetap dipegang oleh lembaga pendidikan formal (Sudarwan Danim, 2006: 69). Untuk itu, dunia pendidikan mempunyai peran ganda, disamping tugas utamanya adalah mendidik peserta didik, juga harus mengajak atau memberi pengetahuan kepada masyarakat secara umum tentang pentingnya menjunjung nilai-nilai akhlak mulia. Atau, dengan bahasa lain, sebagaimana diungkapkan, bahwa “setidaknya ada satu langkah yang tengah ditempuh oleh pemerintah, dengan menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat (school based community). Upaya ini harus dimulai dengan adanya sinergitas antara masyarakat setempat dengan pihak sekolah. Karena diketahui bahwa peserta didik paling lama sehari hanya 7 jam dari 24 jam berada di sekolah atau kampus, sedangkan waktu yang lain mereka gunakan untuk berkumpul bersama keluarga (M. Imam Zamroni, 2004, 213-214)”. Intinya, dunia pendidikan harus mengajak masyarakat, lebih-lebih lingkungan keluarga, untuk ikut menyiapkan SDM yang tangguh, mampu bersaing, dan sekaligus memiliki akhlak mulia. Terkait dengan hal ini, tidak salah apabila meminjam konsep dalam Islam “long life education” (belajar sejak dari pangkuan ibu sampai ke liang lahat). Konsep ini menunjukkan, bahwa pada tahap-tahap awal, khususnya sebelum memasuki bangku sekolah dan sampai dewasa, peran orang tua amatlah krusial serta menentukan dalam menanamkan pada anak tentang nilai-nilai yang perlu dijunjung (A. Fatih Syuhud, 2005). Apalagi era sekarang ini, dengan adanya arus informasi, seperti televisi atau internet, tentu peran keluarga sangat menentukan sebagai pendidik yang pertama, dan harus dapat menunjukkan pada anak-anaknya mana yang positif dan mana yang negatif.
Televisi, tentu mengandung plus dan minus. Satu sisi, televisi adalah sebuah produk kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diakui telah banyak memberikan pengaruh positif dan kemajuan bagi manusia dan kebudayaannya. Misalnya, lewat televisi ide-ide modernisasi dan pembangunan dengan cepat dapat disebarkan ke seluruh pelosok. Televisi dapat dikatakan sebagai salah satu media komunikasi massa yang ampuh dalam menyebarkan pesan-pesan modernisasi dan pembangunan. Melalui televisi dapat dikenalkan nilai-nilai baru yang akan mendukung keberhasilan pembangunan guna kemajuan kebudayaan dan peradaban manusia. Namun, di sisi lain perlu disadari, bahwa televisi juga telah mampu menghentikan aktifitas dan kegiatan manusia, inilah yang sering tidak disadari. Dapat dirasakan, dengan kebiasaan duduk dan berkhayal di depan televisi, timbullah sikap mental pasif, malas, segan mengerjakan ini dan itu. Segalanya ingin serba gampang, seperti yang disaksikan dalam kebanyakan film-film di layar televisi. Televisi telah mendatangkan kesenangan pasif, karena orang akan menjadi terbiasa menonton orang lain bekerja, bermain, ketimbang dia sendiri yang melakukan. Keadaan ini menjadi lebih buruk lagi apabila pihak penyelenggara siaran televise tidak menyadari hal itu, dengan tetap menyiarkan acara-acara yang dapat menambahsuburkan sikap mental semacam itu (Azyumardi Azra, 1998: 169-172).
Keluarga memang memegang peranan yang penting untuk mengarahkan anak-anak, sehingga keberadaan televisi ini bukan malah membuat anak malas akan tetapi sebaliknya. Selanjutnya, perlu diakui bahwa di era sekarang ini kemerosotan akhlak tengah menggejala di tengah-tengah masyarakat. Menurut Sri Hartana (2004), kemerosotan akhlak akibat globalisasi ini ditandai dengan bobroknya perilaku umat manusia. Perilaku malima (madat, main, minum, madon, maling) seolah telah menjadi budaya yang sulit dihindari. Malima seakan menjadi "panglima" dalam sebuah komunitas masyarakat yang sedang "sakit". Banyak orang yang beranggapan di zaman edan ini, yen ora melu ngedan, mangka ora bakal kumanan. Bahkan penelitian BKKBN (Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional) menyebutkan, 30 persen remaja melakukan free sex. Hal ini merupakan temuan mengejutkan sekaligus sangat memprihatinkan. Untuk mencegah hal itu, lingkungan keluarga mempunyai peran penting untuk mengontrol, karena pola pendidikan agama, akhlak, dan perhatian keluarga akan sangat berpengaruh terhadap pergaulan anaknya. Bahkan kini sudah menjadi hal penting, orang tua harus memberikan pendidikan sex yang baik dan benar pada anaknya.
Keluarga merupakan taman pendidikan pertama, terpenting, dan terdekat yang bisa dinikmati anak. Pentingnya peranan orang tua dalam mendidik anak adalah memberikan dasar pendidikan, sikap, watak, dan ketrampilan dasar seperti pendidikan agama, budi-pekerti, sopan-santun, estetika, kasih sayang, rasa aman, dasar-dasar mematuhi peraturan, serta menanamkan kebiasaan-kebiasaan yang baik dan disiplin. Di lingkungan keluargalah seorang anak manusia mengenal nilai dan norma kehidupan. Diketahui, di era globalisasi, dampak budaya dan kemajuan teknologi merupakan wahana “penjajahan” bagi budaya yang dominan. Nilai-nilai budaya dominan ini, yang sebagian besar tidak sesuai dengan timbangan budaya Indonesia, sudah menembus kamar-kamar dan sekeliling masyarakat. Untuk itu, keluarga bisa dimetafora sebagai sebuah benteng yang mampu menciptakan „imunisasi‟ bukan “sterilisasi”(Gunaryadi, 2006).
Demikian pula, menurut Ahmad Tafsir (2004: 155), pendidikan dalam rumah tangga sangatlah strategis dalam pembentukan akhlak dan kepribadian. Tujuan pendidikan dalam rumah tangga adalah agar anak mampu berkembang secara maksimal, yang meliputi seluruh aspek perkembangan anak-anak, yaitu secara jasmani, akal, dan rohani. Tujuan lain ialah membantu sekolah atau lembaga kursus dalam mengembangkan pribadi anak didik. Sementara itu, yang bertindak sebagai pendidik dalam pendidikan rumah tangga adalah ayah-ibu, serta semua orang yang merasa bertanggung jawab terhadap perkembangan anak itu, seperti kakek, nenek, paman, bibi, dan kakak, sekalipun yang paling bertanggung jawab adalah kedua orang tua. Namun, mengingat keterbatasan keluarga, tampaknya tidak semua orang tua mampu mendidik dan mengembangkan anak-anak mereka, baik secara jasmani, akal, maupun rohani. Oleh karena itu, akan lebih baik apabila melirik lembaga pendidikan non formal, seperti Madrasah Diniah (Sekolah Agama), Pondok Pesantren, atau TPA (Taman Pendidikan Al-Qur‟an) sebagai alternatif, yang tampaknya juga penting untuk membantu mengembangkan, khususnya, kematangan rohani. Tentu saja, aktifitas anak-anak yang kurang manfaat di depan layar televisi akan terkurangi apabila mereka di samping belajar di lembaga pendidikan formal, tetapi juga di nonformal. Ambil saja pondok pesantren, di lembaga ini anak-anak akan dibekali pengetahuan agama secara terus-menerus dan berkelanjutan, sehingga diyakini dapat mengantarkan anak didik kepada kematangan rohani.
SIMPULAN
Globalisasi memang sudah tidak dapat ditolak kehadirannya. Globalisasi yang telah merambah kepada semua aspek kehidupan, baik ekonomi, politik, maupun budaya menandakan bahwa orang yang hidup di era ini mau tidak mau harus mampu berkompetisi dalam segala bidang apabila tidak mau tertinggal jauh. Tentu saja, semacam ini merupakan bagian dari tugas dunia pendidikan untuk menyiapkan bagaimana menciptakan SDM yang memiliki kemampuan atau berkompetensi. Jika tujuan pendidikan adalah memiliki arti “suatu daya upaya untuk memajukan budi pekerti, pikiran, dan jasmani agar selaras dengan alam dan mayarakat”, sebagaimana diutarakan oleh Ki Hadjar Dewantara, berarti pada era ini bagaimana dunia pendidikan mampu menyiapkan SDM yang dapat mengikuti “arus globalisasi” dalam arti yang positif. Demikian pula, karena globalisasi mengandung pula hal-hal yang negatif, maka lembaga pendidikan di samping juga masyarakat dan keluarga harus mampu membentengi generasi penerus terutama dari pengaruh budaya yang tidak sesuai dengan norma (agama) sebagai tolak ukur kepribadian atau budi pekerti.
Yang perlu disadari, bahwa globalisasi sebenarnya paradoks dengan dunia pendidikan atau gejala kontra moralitas. Misalnya, satu sisi pendidik harus mengajarkan bagaimana berpakaian yang sopan, santun, dan tidak mengganggu pandangan mata, akan tetapi di sisi lain perkembangan mode, atau gaya pakaian sudah tidak dapat dibendung lagi, bahkan baik media massa maupun elektronik sudah mengarah kepada kebebasan menayangkan gambar-gambar “porno”. Demikian pula, misalnya, pendidik mengajarkan orang harus berhemat, tetapi budaya konsumtif telah mempengaruhi sebagian besar masyarakat. Inilah tantangan dunia pendidikan yang harus dihadapi dalam rangka membentuk manusia yang berbudi pekerti dan mengutamakan nilai-nilai akhlak dalam perilakunya sebagai tujuan utama.
DAFTAR RUJUKAN
- Ahmad Tafsir. 2004. Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam. Bandung: Rosdakarya.
- Al-Zarnuji, Syekh. t. th.. Ta’lim al-Muta’allim Thoriq al-Ta’allum. Semarang: Toha Putra.
- Ardi Kapahang dkk. “Moralitas Kkaum Terdidik: Suatu Tinjauan Filsafat Pendidikan”. Artikel, Oktober 2001.
- http://tumoutou.net/3_sem1_012/ke5_012.htm.
- Azyumardi Azra. (1998). Esei-esei Intelektual Muslim dan Pendidikan Islam. Jakarta: Logos.
- Chomaidi. “Peranan Pendidikan dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Sumeber Daya Manusia”. Disampaikan di depan Rapat Senat Terbuka UNY, 15 Oktober 2005.
- Fatih Syuhud, A. “Tantangan Pendidikan Islam di Era Globalisasi”
- http://afatih.wordpress.com/2005/09/06/
- tantangan-pendidikan-islam-di-era-globalisasi.
- Francis Fukuyama. “Social Capital and Civil Society”,
- http://www.imf.org/external/pubs/ft/seminar/1999/reforms/fukuyama.htm#I
- “Free Seks Masalah Kronis”.
- http://intra.aidsindonesia.or.id/index.php?option=com
- Gunaryadi. (2006). “Pendidikan Nasional, Globalisasi, dan Peranan Keluarga”.
- http://sekolahindonesia.nl/globalisasi-pendidikan.
- Imam Barnadib. (1996). Dasar-dasar Kependidikan: Memahami Makna dan Perspektif Beberapa Teori Pendidikan. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Imam Zamroni, M.. “Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat (Rekonstruksi Sistem Pendidikan Nasional Menuju Pendidikan Berbasis Kerakyatan)”.
- Imam Machali. (2004). Pendidikan Islam dan Tantangan Globalisasi: Buah Pikiran Seputar; Filsafat, Politik, Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Yogyakarta: Ar-Ruzz.
- Irwan Abdullah. (2006). Konstruksi dan Reproduksi Kebudayaan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Jalaluddin Rakhmat. (2003). Islam Aktual: Refleksi Sosial Seorang Cendekiawan Muslim. Bandung: Mizan.
- Mansour Fakih. (2002). Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Miftahuddin. “Konsep Profil Guru dan Siswa: Mengenal Pemikiran al-Zarniji Dalam Ta’lim Al-Muta’allim dan Relevansinya.
- Cakrawala Pendidikan, Juni 2006, Th. XXV, No. 2.
- Mochtar Buchori. 1994. Sepektrum Problematika Pendidikan di Indonesia. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Muhammad Zaenuddin. (2004). Membaca Wacana Intelektual: Perspektif Keagamaan, Sosial-Kemasyarakatan, dan Politik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nurcholish Madjid. (2004). Indonesia Kita. Jakarta: Gramedia. Piötr Sztompka. (2004). Sosiologi Perubahan Sosial.
- Alimandan dari “The Sociology of Social Change”. Jakarta: Prenada.
- Qodri Azizy, A.. (2004). Melawan Globalisasi: Reinterpretasi Ajaran Islam Persiapan SDM dan Terciptanya Masyarakat Madani. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. “Social Capital and Education”.
- http://www1.worldbank.org/prem/poverty/scapital/topic/edu2.htm
- Sudarwan Danim. (2006). Agenda Pembaharuan Sistem Pendidikan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suyanto, “Persoalan Pengangguran dan Pendidikan”
- Kompas, 29 Mei 2004.
- Sri Hartana. (2004). “Reformasi Total dalam Pembinaan Moral”.
- Suara Merdeka, Senin, 27 September.
- Tilaar, H.A.R. (2002). Pendidikan, Kebudayaan, dan Masyarakat Madani Indonesia: Strategi Reformasi Pendidikan Nasional. Bandung: Rosdakarya.

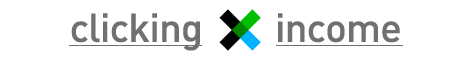





0 komentar:
Posting Komentar