BAB I
PENDAHULUAN
Tidak dapat diragukan lagi bahwa ada pemikiran filsafat yang tumbuh dalam Islam : Mempunyai banyak tokoh dan aliran problematika dan teori, di samping berbagai kekhususan dan keistimewaannya. Filsafat Islam tumbuh dan berkembang dibawah naungan islam, di pengaruhi oleh ajaran-ajarannya dan hidup dibawah suawana peradabannya. Kaum Muslimin, ditimur maupun barat, ikut memberikan andil tanpa memberikan perhitungan adanya perbedaan darah atau tempat tinggal, bahkan tidak ada masalah andaikata pihak non Muslim yang berada di naungan islam ambil bagian.
Pemikiran Filsafat Islam lebih luas dari sekedar terbatas pada aliran-aliran Aristotelisme Arab saja, karena pemikiran Filsafat Islam telah muncul dan di kenal dalam aliran dan teologis (kalamiah) sebelum orang-orang paripatetik (al-Musya’iyyun) dan menjadi tokoh. Dalam ilmu kalam terdapat filsafat, sedangkan filsafat benar-benar menukik dan dalam.
Pandangan para ahli, secara modern Kajian Pemikiran Islam belum tertuju kepada filsafat islam kecuali di tahun-tahun pertama abad ini. Sebagian orientasi dan sekelompok sejarawan mengulas, tetapi tidak memperdalam kajian Filsafat Islam, karena mereka tidak mengetahui sumber-sumbernya dan secara khusus mereka bertumpu pada sebagian rujukan berbahasa latin yang ada. Pada paruh ketiga dari abad ini, kehidupan akademik modern mulai menyerap didunia Arab.
Kemudian, ada tiga model cara berpikir yang berkembang dalam sejarah, dan sekaligus menjadi tolak ukur sebuah kebenaran (benar tidaknya sesuatu), yakni :
1. Model berpikir Rasional Adalah tolak ukur kebenaran yang dilakukan menggunakan akal secara logis.
2. Model berpikir Empirikal Adalah tolak ukur kebenaran yang dilakukan dengan suatu pengamatan dan pengalaman inderawi manusia.
3. Model berpikir Intuitif (Irrasional) Adalah kebenaran dapat digapai lewat pertimbangan-pertimbangan emosional (mukasyafah).
Adapun model berpikir yang umun dipakai dalam kajian Islam yaitu :
(1) Model linguistik atau tekstual (Bayani), model berpikir yang didasarkan atas teks.
(2) Demonstratif (Burhani), metodologinya tidak didasarkan atas teks maupun pengalaman, melainkan atas dasar runtutan nalar logika.
(3) Gnostik / Intuitif (Irfani), model metodologi yang didasarkan atas pendekatan dan pengalaman langsung atas realitas spiritual keagamaan.
BAB II
PEMBAHASAN
Epistemologi
Pemikiran metafisika sejak zaman klasik hingga abad pertengahan telah mendorong filsuf Rene Descartes (1596-1650) untuk memikirkan; ”Bagaimana manusia mendapatkan pengetahuan ?” atau dengan kata lain; ”bagaimana cara para filsuf itu sampai pada kesimpulannya?”. Beberapa pertanyaan inilah yang kemudian disebut dengan persoalan epistemologi.
Istilah epistemologi berasal dari bahasa yunani yaitu episteme yang berarti pengetahuan dan logos yang berarti ilmu, maka epistemologi adalah ilmu tentang pengetahuan. Dari akar kata ini ditarik rumusan epistemologi sebagai berikut : Epistemologi sebagai cabang filsafat yang meyelidiki tentang keaslian, pengertian, struktur, metoda dan validitas ilmu pengetahuan. Selanjutnya Nasution memberikan arti epistemologi : Episteme berarti pengetahuan, dan epistemologi ialah ilmu yang membahas tentang apa itu pengetahuan, dan bagaimana cara memperoleh pengetehuan.
Epistemologi Islam
Apa yang dimaksud dengan epistemologi Islam ? Epistemologi Islam adalah usaha manusia untuk menelaah masalah-masalah obyektivitas, metodologi, sumber serta validitas pengetahuan secara mendalam dengan menggunakan subyek Islam sebagai titik tolak berpikir. Rumusan tersebut membawa dua konsekuensi penting. Di satu sisi epistemologi Islam (arti luas) membahas masalah-masalah epistemologi pada umumnya, sedangkan di sisi lain (ati khusus), epistemologi Islam menyangkut pembicaraan mengenai wahyu dan ilham sebagai sumber pengetahuan dalam Islam.
Perbedaan yang paling mendasar antara epitemologi Barat dan epistemologi Islam terletak pada sumber pengetahuan yang tidak saja bersumber dari akal (rasionalisme) dan pengalaman (empirisme), tetapi pengetahuan pun (dalam Islam) bersumber dari wahyu dan ilham. Wahyu merupakan sumber pertama (primer) bagi Nabi/Rasul untuk memperoleh pengetahuan, sedangkan bagi manusia wahyu merupakan sumber sekunder. Ilham dapat menjadi sumber primer pengetahuan manusia karena dapat diterima oleh setiap manusia yang diberi anugrah Allah.
Dalam Al-Qur’an, Allah menginformasikan mengenai pengetahuan Nabi Muhammad bersumber dari wahyu:
•
Katakanlah: “Aku bukanlah rasul yang pertama di antara rasul-rasul dan aku tidak mengetahui apa yang akan diperbuat kepadaku dan tidak (pula) terhadapmu, aku tidak lain hanyalah mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku dan aku tidak lain hanyalah seoang pemberi peringatan yang menjelaskan” (QS. Al Ahqof : 9).
Ragam Epistemologi Islam
Dalam Islam, terdapat beberapa aliran besar yang berhubungan dengan teori pengetahuan (epistemologi). Sejauh ini ada tiga aliran yang menjadi objek kajian epistemologi Islam, yaitu : Bayani, Irfani, Burhani. Bahkan ada yang menambahkan satu lagi yaitu penalaran Amaly.
Epistemologi Bayani
Pengertian Bayani
Dari kata-kata bahasa Arab, bayan berarti penjelasan. Al-Jabiri, berdasarkan beberapa makna yang diambil dari kamus Lisan al-Arab, suatu kamus karya Ibn Mandzur dan dianggap sebagai karya pertama yang belum tercemari pengertian lain tentang kata ini, memberikan arti sebagai al-fashl wa infishal (memisahkan dan terpisah) dan al-dhuhûr wa al-idhhar (jelas dan penjelasan). Makna al-fashl wa al-idhhâr dalam kaitannya dengan metodologi, sedang infishal wa dhuhûr berkaitan dengan visi (ru`y) dari metode bayani.
Secara terminologi, bayan mempunyai dua arti (1) sebagai aturan-aturan penafsiran wacana (qawanin tafsîr al-khithabi), (2) syarat-syarat memproduksi wacana (syurût intaj al-khithab). Berbeda dengan makna etimologi yang telah ada sejak awal peradaban Islam, makna-makna terminologis ini baru lahir belakangan, yakni pada masa kodifikasi (tadwîn). Antara lain ditandai dengan lahirnya Al-Asybah wa al-Nazhâir fî al-Qur`ân al-Karîm karya Muqatil ibn Sulaiman (w. 767 M) dan Ma`ânî al-Qur`ân karya Ibn Ziyad al-Farra’ (w. 823 M) yang keduanya sama-sama berusaha menjelaskan makna atas kata-kata dan ibarat-ibarat yang ada dalam al-Qur`an.
Menurut Ahmad Khudori Soleh, Bayani adalah metode pemikiran khas Arab yang menekankan otoritas teks (nash), secara langsung atau tidak langsung, dan dijustifikasi oleh akal kebahasaan yang digali lewat istidlal. Secara langsung artinya memahami teks sebagai pengetahuan jadi dan langsung mengaplikasikan tanpa perlu pemikiran. Secara tidak langsung berarti memahami teks sebagai pengetahuan mentah sehingga perlu tafsir dan penalaran. Meski demikian, hal ini tidak berarti akal atau rasio bisa bebas menentukan makna dan maksudnya, tetapi tetap harus bersandar pada teks. Dalam bayani, rasio dianggap tidak mampu memberikan pengetahuan kecuali disandarkan pada teks. Dalam perspektif keagamaan, sasaran bidik metode bayani adalah aspek syariat.
Adapun Teks yang di maksud disini adalah secara umum dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu (1) teks nash (Al Qur’an dan Sunnah Nabi), Al-Qur’an mempunyai otoritas penuh untuk memberikan arah tujuan dan arti kebenaran. Secara singkat dapat dikatakan bahwa epistemologi bayani mendasarkan otoritas pengetahuan langsung dari teks (nash) yang kemudian diimplementasikan pada wilayah praktris tanpa harus melalui pemikiran. Akal tidak dibiarkan “bebas mengembara”, tetapi akal harus berlandaskan teks. (2) teks non nash, yakni karya para ulama’.
Perkembangan Bayani
Pengertian tentang bayani diatas kemudian berkembang sejalan dengan perkembangan pemikiran Islam. Begitu pula aturan-aturan metode yang ada di dalamnya. Pada masa Syafii (767-820 M) yang dianggap sebagai peletak dasar yurisprudensi Islam, bayani berarti nama yang mencakup makna-makna yang mengandung persoalan ushûl (pokok) dan yang berkembang hingga ke cabang (furû`). Sedang dari segi metodologi, Syafii membagi bayan ini dalam lima bagian dan tingkatan.
(1) Bayan yang tidak butuh penjelasan lanjut, berkenaan dengan sesuatu yang telah dijelaskan Tuhan dalam al-Qur`an sebagai ketentuan bagi makhluk-Nya.
(2) Bayan yang beberapa bagiannya masih global sehingga butuh penjelasan Sunnah.
(3) Bayan yang keseluruhannya masih global sehingga butuh penjelasan sunnah.
(4) Bayan Sunnah, sebagai uraian atas sesuatu yang tidak terdapat dalam al-Qur`an.
(5) Bayan Ijtihad, yang dilakukan dengan qiyas atas sesuatu yang tidak terdapat dalam al-Qur`an maupun Sunnah.
Dari lima derajat bayan tersebut al-Syafi’i kemudian menyatakan bahwa yang pokok (ushûl) ada tiga, yakni al-Qur`an, Sunnah dan Qiyas, kemudian ditambah ijma.
Al-Jahizh (w. 868 M) yang datang berikutnya mengkritik konsep bayan Syafii di atas. Menurutnya, apa yang dilakukan Syafii baru pada tahap bagaimana memahami teks, belum pada tahap bagaimana memberikan pemahaman pada pendengar atas pemahaman yang diperoleh. Padahal, menurutnya, inilah yang terpenting dari proses bayani. Karena itu, sesuai dengan asumsinya bahwa bayan adalah syarat-syarat untuk memproduksi wacana (syurut intâj al-khithab) dan bukan sekedar aturan-aturan penafsiran wacana (qawânin tafsîr al-khithabi), Jahizh menetapkan syarat bagi bayani. Yaitu :
(1) Syarat kefasihan ucapan.
(2) Seleksi huruf dan lafat, sehingga apa yang disampaikan bisa menjadi tepat guna.
(3) Adanya keterbukaan makna, yakni bahwa makna harus bisa diungkap dengan salah satu dari lima bentuk penjelas, yakni lafat, isyarat, tulisan, keyakinan dan nisbah.
(4) Adanya kesesuaian antara kata dan makna.
(5) Adanya kekuatan kalimat untuk memaksa lawan mengakui kebenaran yang disampaikan dan mengakui kelemahan serta kesalahan konsepnya sendiri.
Sampai di sini, bayani telah berkembang jauh. Ia tidak lagi sebagai sekedar penjelas atas kata-kata sulit dalam al-Qur`an tetapi telah berubah menjadi sebuah metode bagaimana memahami sebuah teks (nash), membuat kesimpulan dan keputusan atasnya, kemudian memberikan uraian secara sistematis atas pemahaman tersebut kepada pendengar, bahkan telah ditarik sebagai alat untuk memenangkan perdebatan. Namun, apa yang ditetapkan al-Jahizh dalam rangka memberikan uraian pada pendengar tersebut, pada masa berikutnya, dianggap kurang tepat dan sistematis. Menurut Ibn Wahhab , bayani bukan diarahkan untuk ‘mendidik’ pendengar tetapi sebuah metode untuk membangun konsep diatas dasar ashul-furu`; caranya dengan menggunakan paduan pola yang dipakai ulama fiqh dan kalâm (teologi).
Paduan antara metode fiqh yang eksplanatoris (keterangan yang bersifat menjelaskan) dan teologi yang dialektik dalam rangka membangun epistemologi bayani baru ini sangat penting, karena menurutnya, apa yang perlu penjelasan (bayan) tidak hanya teks suci tetapi mencakup empat hal. Yaitu :
(1) Wujud materi yang mengandung aksiden dan substansi.
(2) Rahasia hati yang memberi keputusan bahwa sesuatu itu benar-salah dan subhat, saat terjadi proses perenungan.
(3) Teks suci dan ucapan yang mengandung banyak dimensi.
(4) Teks-teks yang merupakan representasi pemikiran dan konsep.
Dari empat macam objek ini, Ibn Wahhab menawarkan empat macam bayani :
(1) Bayân al-I`tibar untuk menjelaskan sesuatu yang berkaitan dengan materi.
(2) Bayan al-I`tiqad berkaitan dengan hati (qalb).
(3) Bayan al-`ibarah berkaitan dengan teks dan bahasa.
(4) Bayan al-kitab berkaitan dengan konsep-konsep tertulis.
Pada periode terakhir muncul al-Syathibi (w. 1388 M). Sampai sejauh itu, menurutnya, bayani belum bisa memberikan pengetahuan yang pasti (qath`I) tapi baru derajat dugaan (zhan), sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan secara rasional. Dua teori utama dalam bayani, istimbath dan qiyas, yang dikembangkan bayani hanya berpijak pada sesuatu yang masih bersifat dugaan. Padahal, penetapan hukum tidak bisa didasarkan pada sesuatu yang bersifat dugaan.
Karena itu, Syathibi lantas menawarkan tiga teori untuk memperbarui bayani, yakni al-istintaj, al-istiqra’ dan maqâshid al-syari`, yang dieleminir dari pemikiran Ibn Rusyd dan Ibn Hazm. Al-Istintaj sama dengan silogisme, menarik kesimpulan berdasarkan dua premis yang mendahului, berbeda dengan qiyas bayani yang dilakukan dengan cara menyandarkan furu` pada ashl, yang oleh Syathibi dianggap tidak menghasilkan pengetahuan baru. Pengetahuan bayani harus dihasilkan melalui proses silogisme ini, sebab menurut al-Syâthibi, semua dalil syara` telah mengandung dua premis, nazhariyah (teoritis) dan naqliyah (transmisif). Nazhariyah berbasis pada indera, rasio, penelitian dan penalaran, sementara naqliyah berbasis pada proses transmisif (naql/ khabar). Nazhariyah merujuk pada tahqîq al-manâth al-hukm (uji empiris suatu sebab hukum) dalam setiap kasus, sedang naqliyah merujuk pada hukum itu sendiri dan mencakup pada semua kasus yang sejenis, sehingga ia merupakan kelaziman yang tidak terbantah dan sesuatu yang mesti diterima. Nazhariyah merupakan premis minor sedang naqliyah menjadi premis mayor. Istiqra’ adalah penelitian terhadap teks-teks yang setema kemudian di ambil tema pokoknya, tidak berbeda dengan tematic induction. Sedang maqâshid al-syar`iyah berarti bahwa diturunkannya syariah ini mempunyai tujuan-tujuan tertentu, yang menurut Syathibi terbagi dalam tiga macam; dlarûriyah (primer), hajiyah (sekunder) dan tahsîniyah (tersier).
Pada tahap ini, metode bayani telah lebih sempurna dan sitematis, dimana proses pengambilan hukum atau pengetahuan tidak sekedar mengqiyaskan furu` pada ashl tetapi juga lewat proses silogisme seperti dalam filsafat.
Bayani Sebagai Sumber Pengetahuan
Meski menggunakan metode rasional filsafat seperti digagas Syathibi, epistemology bayani tetap berpijak pada teks (nash). Dalam ushûl al-fiqh, yang dimaksud nash sebagai sumber pengetahuan bayani adalah al-Qur`an dan hadis. Ini berbeda dengan pengetahuan burhani yang mendasarkan diri pada rasio dan irfani pada intuisi. Karena itu, epistemolog bayani menaruh perhatian besar dan teliti pada proses transmisi teks dari generasi ke generasi.
Persoalan di atas sangat penting bagi bayani, karena sebagai sumber pengetahuan benar tidaknya transmisi teks menentukan benar salahnya ketentuan hukum yang diambil. Jika transmisi teks bisa di pertanggungjawabkan berarti teks tersebut benar dan bisa dijadikan dasar hukum. Sebaliknya, jika transmisinya diragukan, maka kebenaran teks tidak bisa dipertanggungjawabkan dan itu berarti ia tidak bisa dijadikan landasan hukum.
Karena itu, mengapa pada masa tadwîn (kodifikasi), khususnya kodifikasi hadis, para ilmuan begitu ketat dalam menyeleksi sebuah teks yang diterima. Bukhari, misalnya, menggariskan syarat yang tegas bagi diterimanya sebuah teks hadis; (1) Bahwa perowi harus memenuhi tingkat kriteria yang paling tinggi dalam hal watak pribadi, keilmuan dan standar akademis, (2) Harus ada informasi positif tentang para perowi yang menerangkan bahwa mereka saling bertemu muka dan para murid belajar langsung pada gurunya. Dari upaya-upaya seleksi tersebut kemudian lahir ilmu-ilmu tertentu untuk mendeteksi dan memastikan keaslian teks, seperti al-Jarh wa al-Ta`dîl, Mushthalah al-Hadits, Rijal al-Hadits dan seterusnya.
Selanjutnya, tentang nash al-Qur`an, meski sebagai sumber utama, tetapi ia tidak selalu memberikan ketentuan pasti. Dari segi penunjukkan hukumnya (dilâlah al-hukm), nash al-Qur`an bisa dibagi dua bagian, qath`I dan zhanni. Nash yang qath`I dilâlah adalah nash-nash yang menunjukkan adanya makna yang dapat difahami dengan pemahaman tertentu, atau nash yang tidak mungkin menerima tafsir dan takwil, atau sebuah teks yang tidak mempunyai arti lain kecuali arti yang satu itu. Dalam konsep Syafi`i, ini yang disebut bayan yang tidak butuh penjelasan lanjut. Nash yang dzanni dilâlah adalah nash-nash yang menunjukkan atas makna tapi masih memungkinkan adanya takwil, atau dirubah dari makna asalnya menjadi makna yang lain.
Kenyataan tersebut juga terjadi pada al-sunnah, bahkan lebih luas. Jika dalam al-Qur`an, konsep qath’I dan dzanni hanya berkaitan dengan dilâlah-nya, dalam sunnah hal itu berlaku pada riwayat dan dilâlah-nya. Dari segi riwayat berarti bahwa teks hadis tersebut diyakini benar-benar dari Nabi atau tidak, atau bahwa aspek ini akan menentukan sah tidaknya proses transmisi teks hadis, yang dari sana kemudian lahir berbagai macam kualitas hadis, seperti mutawatir, ahad, shahîh, hasan, gharîb, ma`rûf, maqtû` dan seterusnya. Dari segi dilâlah berarti bahwa makna teks hadis tersebut telah memberikan makna yang pasti atau masih bisa ditakwil.
Cara Bayani Mendapatkan Pengetahuan
Untuk mendapatkan pengetahuan, epistemologi bayani menempuh dua jalan. Pertama, berpegang pada redaksi (lafat) teks dengan menggunakan kaidah bahasa Arab, seperti nahwu dan sharâf sebagai alat analisa. Kedua, menggunakan metode qiyâs (analogi) dan inilah prinsip utama epistemologi bayani.
Dalam kajian ushûl al-fiqh, qiyas diartikan sebagai memberikan keputusan hukum suatu masalah berdasarkan masalah lain yang telah ada kepastian hukumnya dalam teks, karena adanya kesamaan illah. Ada beberapa hal atau ruku-rukun yang harus dipenuhi dalam melakukan qiyas :
(1) Al-ashl, yakni masalah yang telah ditetapkan hukumnya baik dalam Al-Qu’an atau dalam sunnah rasulullah. Ashal disebut juga al-maqis ‘alaih (tempat mengiaskan sesuatu).
(2) Al-far`, sesuatu yang tidak ada ketegasan hukumnya dalam Al-Qur’an, Sunnah, atau ijma’.
(3) Hukm al-ashl, yakni hukum syara’ yang terdapat pada ashal yang hendak ditetapkan pada far’ dengan jalan qiyas.
(4) Illah, rukun yang satu ini merupakn inti dari praktik qiyas. Karena berdasarkan illah itulah hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah dapat di kembangkan. Illah menurut bahasa berarti “sesuatu yang mengubah keadaan”, misalnya penyakit disebut illah karena sifatnya mengubah kondisi seseorang yang terkena penyakit itu.
Contoh qiyas adalah soal hukum meminum arak dari kurma. Arak dari perasan kurma disebut far` (cabang) karena tidak ada ketentuan hukumnya dalam nash, dan ia akan diqiyaskan pada khamer. Khamer adalah ashl (pokok) sebab terdapat dalam teks (nash) dan hukumnya haram, alasannya (illah) karena memabukkan. Hasilnya, arak adalah haram karena ada persamaan antara arak dan khamer, yakni sama-sama memabukkan.
Menurut Jabiri, metode qiyas sebagai cara mendapatkan pengetahuan dalam epistemologi bayani tersebut digunakan dalam tiga aspek.
Pertama, qiyas dalam kaitannya dengan status dan derajat hukum yang ada pada ashl maupun furû` (al-qiyâs bi i`tibâr madiy istihqâq kullin min al-ashl wa al-far`i li al-hukm). Bagian ini mencakup tiga hal:
1. Qiyas jalî, dimana far` mempunyai persoalan hukum yang kuat dibanding ashl.
2. Qiyas fî ma`na al-nash, dimana ashl dan far` mempunyai derajat hukum yang sama.
3. Qiyas al-khafî, dimana illat ashl tidak diketahui secara jelas dan hanya menurut perkiraan mujtahid. Contoh qiyâs jalî adalah seperti hukum memukul orang tua (far`). Masalah ini tidak ada hukumnya dalam nash, sedang yang ada adalah larangan berkata “Ah” (ashl). Perbuatan memukul lebih berat hukumnya dibanding berkata “ah”.
Kedua, berkaitan dengan illat yang ada pada ashl dan far`, atau yang menunjukkan kearah situ (qiyâs bi i`tibâr binâ’ al-hukm alâ dzikr al-illah au bi i`tibâr dzikr mâ yadull `alaihâ). Bagian ini meliputi dua hal:
1. Qiyâs al-illat, yaitu menetapkan ilat yang ada ashl kepada far’.
2. Qiyâs al-dilâlah, yaitu menetapkan petunjuk (dilâlah) yang ada pada ashl kepada far`, bukan illahnya.
Ketiga, qiyas berkaitan dengan potensi atau kecenderungan untuk menyatukan antara ashl dan far` (qiyâs bi i`tibâr quwwah “al-jâmi`” bain al-ashl wa al-far` fayumkin tashnifuh) yang oleh al-Ghazali dibagi dalam empat tingkat: (1) adanya perubahan hukum baru, (2) keserasian, (3) keserupaan (syibh), (4) menjauhkan (thard).
Menurut Abd al-Jabbar, seorang pemikir teologi Muktazilah, metode qiyas bayani diatas tidak hanya untuk menggali pengetahuan dari teks tetapi juga bisa dikembangkan dan digunakan untuk mengungkap persoalan-persoalan non-fisik (ghaib). Disini ada empat cara.
1. Berdasarkan kesamaan petunjuk (dilâlah) yang ada (istidlâl bi al-syâhid alâ al-ghâib li isytirâkihimâ fî al-dilâlah). Contoh, untuk mengetahui bahwa Tuhan Maha Berkehendak. Kehendak Tuhan (ghaib) diqiyaskan pada kondisi empirik manusia (syahid). Hasilnya, ketika dalam realitas empirik manusia mempunyai kehendak dan tindakan berarti Tuhan juga demikian.
2. Berdasarkan kesamaan illah (istidlâl bi al-syâhid alâ al-ghâib li isytirâkihimâ fî al-illah). Contoh, Tuhan tidak mungkin berlaku jahat karena pengetahuan-Nya tentang hal tersebut. Ini didasarkan atas kenyataan yang terjadi pada manusia, yaitu ketika manusia tidak akan berbuat jahat karena mengetahui tentang kejelekan sikap tersebut, berarti Tuhan juga demikian.
3. Berdasarkan kesamaan yang berlaku pada tempat ilah (istidlâl bi al-syâhid alâ al-ghâib li isytirâkihimâ fîmâ yajrî majra al-illah).
4. Berdasarkan pemahaman bahwa yang ghaib mempunyai derajat lebih dibanding yang empirik (istidlâl bi al-syâhid alâ al-ghâib li kaun al-hukm fî al-ghâib ablagh minh fî al-syâhid). Contoh, ketika mengetahui bahwa kita (syahid) harus berlaku baik karena hal tersebut adalah kebaikan, maka apalagi Tuhan yang maha mengetahui bahwa sesuatu adalah baik.
Kritik Epistemologi Bayani
Kritik yang sering dialamatkan kepada metode bayani, di mana suatu teks belum tentu diterima secara universal. Oleh karena itu ketika berhadapan dengan pertentangan seperti itu, nalar bayani biasanya cenderung mengambil sikap dogmatik, defensif, apologetik dan polemis. Artinya menempatkan teks yang dikaji sebagai suatu ajaran mutlak (dogma) yang harus dipatuhi, diikuti, diamalkan, tidak boleh diperdebatkan, apalagi ditolak.
Walaupun Islam memerlukan nalar bayani, namun di sisi lain penggunaan nalar bayani secara berlebihan akan menimbulkan permasalahan baru, yaitu kurang bisa dinamis mengikuti perkembangan sejarah dan sosial masyarakat yang begitu cepat berubah. Faktanya, pemikiran Islam saat ini yang masih banyak didominasi pemikiran bayani fiqhiyyah kurang bisa merespon dan mengimbangi perkembangan peradaban dunia. Dengan begitu, mestinya kajian model ini diperkuat dengan analisis konteks, bahkan kontekstualisasi (relevansi).
BAB III
PENUTUP
Kesimpulan
Berdasarkan uraian di atas. Pertama, Bayani adalah sebuah motodologi berpikir yang didasarkan atas teks. Dalam burhani Al-Qur’an mempunyai otoritas penuh untuk memberikan arah tujuan dan arti kebenaran. Sedangkan rasio menurut metodologi ini hanya berperan-fungsi sebagai pengawal bagi keamanan otoritas teks tersebut.
Kedua, perbedaan yang paling mendasar antara epitemologi Barat dan epistemologi Islam terletak pada sumber pengetahuan yang tidak saja bersumber dari akal (rasionalisme) dan pengalaman (empirisme), tetapi pengetahuan pun (dalam Islam) bersumber dari wahyu dan ilham.
Ketiga, bahwa secara historis, bayani berkembang dari “bawah”, dari sekedar upaya memisahkan kata-kata al-Qur`an dari pengaruh kata-kata asing dan menjelaskan kata-katanya yang sulit sampai menjadi metode berfikir yang sistematis untuk menggali pengetahuan dan menyampaikannya kepada pendengar.
Keempat, bahwa sumber pengetahuan bayani, al-Qur`an dan sunnah, tidak senantiasa bersifat pasti (qath`I) tetapi terkadang juga samar (zhanni), bahkan sunnah bersifat qath`I dan zhanni dari segi materi maupun transmisi teksnya. Persoalan pokok yang diangkat mencakup dua hal, lafat-makna dan ushûl-furû`. Segi lafat-makna, bahwa lafat atau kata muncul lebih dahulu dan menentukan makna yang dimaksud, bahkan juga menentukan sistem berfikir selanjutnya. Sedang segi ushûl-furû`, bahwa ashl bisa berkedudukan sebagai sumber, sandaran atau pangkal dari proses penbentukan pengetahuan.
Kelima, pengetahuan bayani diperoleh lewat dua cara atau tahapan, (1) berdasarkan susunan redaksi teks yang dikaji lewat analisa linguistik, (2) berdasarkan metode qiyas atau analogi yang dilihat dari salah satu dari tiga aspek, yaitu hubungan antara ashl dan far, illat yang ada pada ashl dan far`, dan kecenderungan yang menyatukan antara ashl dan far`.
Keenam, analogi bayani tidak hanya digunakan untuk menggali pengetahuan dari teks melainkan juga dipakai untuk memahami realitas-realitas non-fisik. Pengetahuan dan teori-teori metafisik-teologis Islam klasik didasarkan atas metode qiyas bayani ini.
Ketujuh, karena hanya mendasarkan diri pada teks, pemikiran bayani menjadi “terbatas” dan terfokus pada hal-hal yang bersifat aksidental bukan substansial, sehingga kurang bisa dinamis mengikuti perkembangan sejarah dan sosial masyarakat yang begini cepat. Kenyataannya, pemikiran Islam saat ini yang masih banyak didominasi bayani fiqhiyah kurang bisa merespon dan mengimbangi perkembangan peradaban dunia. Yang semestinya kajian model ini diperkuat dengan analisis konteks, bahkan kontekstualisasi (relevansi).
Kritik dan Saran
Penulisan makalah ini masih banyak kekurangan, oleh sebab itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang dapat membangun, demi kesempurnaan makalah ini.
DAFTAR PUSTAKA
Madkour, Ibrahim, 1995. Aliran dan Teori Filsafat Islam. Jakarta : Bumi Aksara.
Al-Jabiri, 1991. Bunyah al-Aql al-Arabi. Beirut, al-Markaz al-Tsaqafi al-Arabi.
Nasution, khoiruddin, 2009. Pengantar Studi Islam. Yogyakarta, ACAdeMIA + TAZZAFA.
Jamil, Fathur Rahman, 1997. Filsafat Hukum Islam. Jakarta, Logos.
Nasution, Harun, 1973. Falsafat Agama. Jakarta, Bulan Bintang.
Khalaf, Abdul Wahab, 1996. Ilmu Ushul Fiqh (Terjemahan Masdar Helmi. Bandung: Gema Risalah Pres.
Khalaf, Abdul Wahab, 1996. Ilmu Ushul Fiqh.
Effendi, Satria. Zein, Ushul Fiqh (Jakarta, Kencana 2008).
Muslih, Mohammad, 2005. Filsafat Umum dalam pemahaman praktis. Yogyakarta, Belukar Gowok.

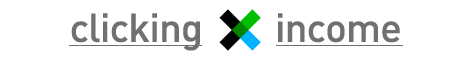





0 komentar:
Posting Komentar